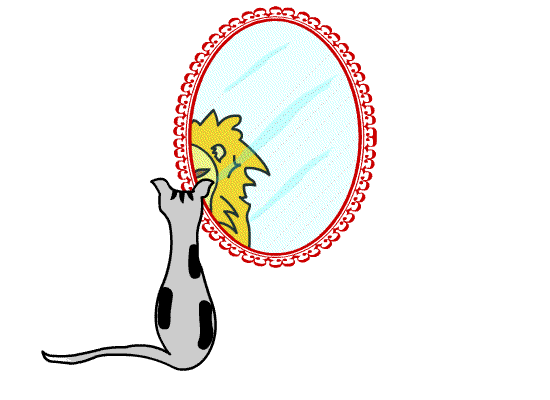Ini sudah senja kesembilan sejak kakeknya pergi. Tak jua ada kabar, andai saja dia tetap memaksa kakek membawa telepon genggam itu. Pasti tak begini kejadiannya.
Merutuki diri adalah hal yang paling sering dilakukannya akhir-akhir ini.
“Tak perlulah bawa-bawa henpon, kakek ini ndak tau cara menggunakannnya.”
“Tapi, kek,,” Kalimatnya itu menggantung diawang-awang saja. Kalau sikakek sudah mengibaskan tangan, pertanda tak ingin ditentang!
*****
Dia baru pulang dari pasar mengantarkan pesanan kue langganan. Kakinya menumbuk onggokan kertas disepan pintu. Ada tiga!
Kertas pertama, amplop putih. Sudah pasti tagihan listrik, diabaikan, sudah biasa. Amplop kedua, sedikit menarik perhatian. Berwarna cokelat dengan stempel pos dan, lambang negara? Nama tertuju adalah nama kakeknya, tak salah lagi. Amplop ketiga sudah jauh kalah penting.
*****
“Jadi pergi kan, kek?” Kakeknya diamsaja sambil mendengarkan suara kemerosok siaran berita. RRI lagi.
Lama tak ada sahutan. “Kakek sudah terlalu tua berjalan jauh.”
Dicobanya rayuan berikutnya. “Kek, tak banyak pahlawan dinegeri ini yang diperhatikan pemerintah. Biasanya hanya dikenal pas jaman perjuangan, habis itu, kaki patah demi negara pun tak digubris.”
Sikakek makin mempercepat goyangan kursi malasnya. “Nanti kita bicarakan lagi!”
*****
Tak perlu koper, kata kakeknya. Baju hanya tiga potong saja. Kemeja lengan panjang dengan celana berbahan kain. Balsem, tancho merk minyak rambut andalan, semir sepatu, kain sarung dan peci. Hanya itu. Tak ada pasta gigi dan sikatnya.
Dia lega sekali, kakeknya akan menghadiri upacara kemerdekaan di Istana Negara. Bergabung dengan veteran lainnya. Diundang langsung oleh Negara, betapa hebat kakeknya! Kakeknya yang diundang ke Istana Negara, tapi dia yang bangga. Tak apalah, kakek pasti pejuang yang hebat dizamannya. Sekali lagi dia sumringah.
*****
Sumringahnya lenyap hingga pada hari kedua setelah acara kehormatan itu usai, kakek belum juga kembali. Ada perasaan tak tenang mengusiknya! Entah apa. Bolak-balik dia merutuki diri.
Dia menenangkan diri sejenak. Mungkin kakek pulang besok. Hiburnya pada diri sendiri.
*****
Upacara Kenegaraan memperingati hari merdekanya negeri ini, akan dimulai besok pagi. Para pahlawan yang diundang telah menempati kamar terbaik sebagai bentuk penghargaan akan jasa mereka dahulu.
Lelaki tua pertengahan delapan puluh itu tetap tak bisa tidur nyenyak. Ada perasaan mengganjal dihatinya.
*****
Upacara kenegaraan itu telah usai. Sesosok lelaki tua berjalan sendiri memisahkan diri dari rombongan sejak subuh. Tak tau kemana akan pergi, di turuti saja kaki melangkah.
Selembar daun kering melayang didepan wajah lelaki tua itu. Berwarna coklat. Di pungutnya, dengan sekali genggaman, daun itu remuk. Sebuah kenangan dimasa lalu terkuak, membuka kenangan.
*****
“Apa yang kau bawa pada kami, sersan Herman?” Hardik lelaki Belanda berperawakan besar.
Lelaki yang bernama Herman itu senyum, “Ada sekitar lima belas prajurit yang akan melintasi perbatasan, tuan. Mereka akan berpakaian layaknya rakyat sipil. Merekalah yang patut dibunuh, mereka itu pasukan mata-mata untuk Endonesia.”
Lelaki yang bertanya melemparkan beberapa keping uang tepat kehadapannya. Berwarna coklat. Sejak itu dia mengasingkan diri.
Beberapa hari kemudian, serbuan yang telah direncanakan diam-diam berhasil dipatahkan si Penjajah. Lima belas tentara keamanan ditemukan tergeletak bersimbah darah dengan bagian tubuh yang terpisah. Mati!"
*****
Lelaki itu menghela nafas, panjang sekali. Angin yang bertiup mendirikan bulu kuduknya.
“Aku tau, kau pelakunya Herman! Yang mati itu harusnya kau, Herman!” Pelipsnya disodok pucuk senapan.
Malaikat penunda maut menjelma dalam sosok disebelahnya. “Sersan Andi, tahan. Biarkan saja, dia tak perlu mati! Penghianat seperti dia, sudah mati sejak pertama menggadaikan negerinya pada tumpukan uang!”
Lelaki yang menodongkan pistol itu nampak berang, tangannya sampai bergemetar. Perintah dari atasan itu mengurungkan niatnya. Dia tak mati hari ini.
*****
Dada lelaki itu semakin sesak. Dia hidup menikmati kemerdekaan hingga hari ini, justru saat dia menghianati negeri sendiri. Entah bagaimana bisa.
Mungkin cucunya akan kecewa jika tau, semoga saja semua teman-temannya sudah mati, hingga tak ada aib yang disembunyikan lagi.
Atau dia yang harusnya sejak lama mati. Ujung sepatunya menghantam batu besar, ditimangnya dengan telapak tangan kirinya. Berat, cukup sekali hantaman kekepala, pasti langsung mati!